Masih dalam rangka menantang
diri di proyek #NulisRandom2015, ternyata baru hari ke dua sudah miskin ide.
Untungnya ada banyak buku di rak, yang belum sempat dibuat resensinya. Jadi
tampaknya, kelanjutan proyek ini ke depan adalah berjuang mencari ide, lalu
kalau sudah mentok ambil buku secara acak dari lemari dan membuat resensi.
Memaksa diri membaca ulang setiap buku dan menggali lebih dalam, rasanya tak
ada jeleknya untuk orang yang bermimpi jadi penulis seperti saya.
Buku yang akan saya bahas kali
ini adalah The Geography of Bliss: Kisah
Seorang Penggerutu yang Berkeliling Dunia Mencari Negara Paling Membahagiakan.
Buku ini ditulis oleh Eric Weiner, seorang jurnalis berkebangsaan Amerika
Serikat, dan diterjemahkan oleh M. Rudi Atmoko untuk Penerbit Qanita, 2014.
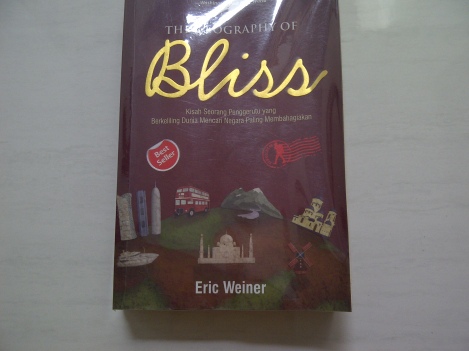
Awalnya saya mengira buku ini
adalah semacam buku traveling yang
akan membawa pembaca keliling dunia sebagai wisatawan, disertai deskripsi dan
aneka tips tentang masing-masing tujuan wisata di berbagai negara. Ternyata
buku ini bukan panduan untuk para pelancong, melainkan untuk para pencari
kebahagiaan. Eric Weiner mengajak pembaca berkeliling dunia sambil mengkaji
negara mana yang penduduknya paling bahagia dan mana yang paling tak berbahagia.
Saat penulis lain banyak membedah makna kebahagiaan, Weiner menandai di mana letak kebahagiaan dalam peta
dunia.
Ada sepuluh negara yang
dikunjungi Weiner dalam penyusunan buku ini. Tentu saja keragaman budaya dan
cara hidup masyarakat masing-masing negara membuat persepsi tentang kebahagiaan
juga tak seragam. Namun pada dasarnya semua manusia tahu apakah dirinya bahagia
atau tidak. Musababnya bisa beraneka, namun rasa
bahagia dapat dikenali sebagaimana rasa lapar atau jatuh cinta.
Saya tak akan membahas
masing-masing negara secara berurutan sebagaimana format buku ini. Akan saya
rangkum berdasar pertanyaan yang sering terlintas di benak saya tentang
kebahagiaan.
Pertama, apakah kebebasan membuat orang bahagia? Kita bisa tanyakan ini
kepada orang Belanda. Di negara ini, kebebasan sangat dihormati. Ganja dan
prostitusi yang di negara lain bisa membuat seseorang dijatuhi hukuman mati, di
Belanda legal. Toko-toko khusus dewasa, café yang bisa dikunjungi penduduk
maupun turis untuk nge-fly,
berdampingan dengan para imigran asal timur tengah berbusana tertutup yang
cukup banyak mengisi kota-kota besar di Belanda. Kepercayaan yang berlawanan
tidak menghasilkan pertikaian atau ketegangan.
Weiner membahasnya dengan
profesor ahli kebahagiaan di Belanda. Kebahagiaan jelas berbeda dengan
kesenangan. Toleransi itu sangat bagus, tapi bisa dengan mudah bergeser ke
ketidakpedulian, dan itu sama sekali tidak menyenangkan. Begitu banyak
kelonggaran tidak secara otomatis menjadikan orang bahagia. Ini berlawanan
dengan apa yang disangka oleh mereka yang merindukan kebebasan mutlak.
Pertanyaan berikutnya, apakah uang membuat orang bahagia? Untuk
menjawab hal ini, kita bisa berkunjung ke Qatar. Negara yang dulunya padang
pasir gersang menjelma jadi salah satu negara super kaya berkat minyak.
Orang-orangnya pun para individu super kaya yang hidup dengan standar tinggi.
Kita tak akan menemukan sopir, pramuniaga, asisten rumah tangga, dan pekerjaan
‘rendahan’ semacam itu dikerjakan oleh orang Qatar. Semua pekerjaan itu diisi
oleh para imigran dari negara yang tak terlalu kaya. Bahkan para awak pesawat,
paramedis dan dosen pun mereka impor dari negara lain. Lalu di mana orang-orang
Qatar? Menikmati kekayaannya, tentu.
Seperti orang kaya baru yang
memenangkan lotre, orang Qatar menikmati menjadi kaya dengan cara yang
berlebihan. Tak ada gedung yang tak mewah, tak ada fasilitas yang tidak luar
biasa. Tapi, menurut Weiner, tak berjiwa. Hubungan antar manusianya, mentalitas
‘majikan’ yang menganggap semua orang asing pegawai yang bisa dibayar,
persaingan antar suku atau keluarga bagai api dalam sekam. Di Qatar, uang
berhasil membeli kemewahan, tapi tidak kebahagiaan.
Weiner tidak memasukkan
negara-negara super miskin di Afrika dalam catatan perjalanan ini. Menurutnya,
akan menjadi bias mengukur kebahagiaan di tempat yang kebutuhan dasar manusia
seperti makan dan air belum terpenuhi. Namun Weiner mengunjungi sebuah negara
yang hampir selalu menempati urutan terbawah pada indeks kebahagiaan. Negara
ini tidak terletak di Afrika atau Asia, tapi di Eropa.
Moldova adalah negara yang penduduknya sangat
murung dan menyimpan ketidakpuasan pada banyak hal. Tidak ada peperangan atau
konflik berarti di Moldova. Kemiskinan memang terasa, tapi tentu masih jauh di
atas Nigeria atau Bangladesh. Masalahnya, orang Moldova tidak membandingkan
diri dengan Nigeria dan Bangladesh. Mereka membandingkan diri dengan Jerman dan
Italia. Jadi, apakah uang membawa kebahagiaan? Mungkin jawabannya: tergantung seberapa kaya
tetanggamu.
Lalu ada apa di negara yang paling bahagia? Di kepala sebagian orang
barat, tempat yang membahagiakan adalah matahari sepanjang tahun, pantai yang
indah untuk bersantai. Ternyata negara yang langganan memuncaki indeks
kebahagiaan adalah Islandia, tempat penuh es yang dianaktirikan oleh matahari.
Makanannya pun rasanya aneh, menurut penulis. Di negara ini seorang presiden
tidak akan didemo jika tingkat inflasi naik, namun akan diprotes jika angka
pengangguran bertambah. Inflasi tentu tidak menyenangkan, tapi semua orang
merasakan bersama. Pengangguran menciptakan kesenjangan, dan itu salah satu
sumber ketidakbahagiaan.
Islandia adalah negara yang
dipenuhi oleh orang-orang gagal. Musisi yang tak kunjung masuk industri
rekaman, penulis yang tak terkenal, pelukis dan pematung yang biasa-biasa saja.
Tapi iklim kreatif di negeri ini sangat pekat. Rasa seni dan pengembangan
budaya subur di mana-mana. Hebatnya, kegagalan dianggap sesuatu yang bagus.
Orang-orang Islandia sangat menghargai proses, usaha seseorang dan bukan hasil
akhirnya. Weiner meyakini bahwa salah satu sumber kebahagiaan Islandia adalah
langkanya rasa iri. Jika sebuah band memerlukan gitar atau pengeras suara, band
lain akan segera membantu tanpa bertanya. Budaya apresiasi, bukan kompetisi,
menjauhkan rasa iri.
Untuk saya pribadi, negara yang
paling menarik adalah Bhutan. Sebuah negara yang jarang terdengar, letaknya
tersembunyi di balik pegunungan tinggi Himalaya. Di Bhutan, kebahagiaan adalah
kebijakan negara. Saat negara lain menggunakan PDB sebagai indeks
keberhasilannya sebagai negara, Bhutan menetapkan Kebahagiaan Nasional Bruto
(KNB). Pemerintah dipandang gagal kalau warganya tidak bahagia.
Untungnya, rakyat Bhutan adalah
orang-orang bahagia. Bukan karena sangat kaya atau punya kebebasan individu
yang penuh. Kebahagiaan menurut definisi Bhutan adalah mengetahui berbagai keterbatasan Anda, mengetahui seberapa banyak
adalah cukup. Kebahagiaan tidak bersifat individu, tapi komunal. Orang
Bhutan menghargai hubungan dan harmoni. Bagi
rakyat Bhutan, kebahagiaan adalah usaha bersama.
Mungkin karena saya orang Asia,
maka ide tentang bahagia sebagai sebuah harmoni lebih menarik bagi saya
ketimbang konsep kebahagiaan individu. Kebahagiaan lebih bersifat spiritual
daripada kebendaan atau kesenangan hedonisme.
Secara keseluruhan, Weiner
menyajikan kisahnya dengan menarik. Jika buku traveling lain membuat orang ingin berkunjung ke tempat yang
ditulis, buku ini memberikan efek yang berbeda. Bliss justru membuat pembaca merasa tertantang untuk menempuh
perjalanan ke dalam diri sendiri, dan bertanya: apakah kau bahagia?
Bagi saya, jawabannya adalah:
Ya, saya bahagia!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar