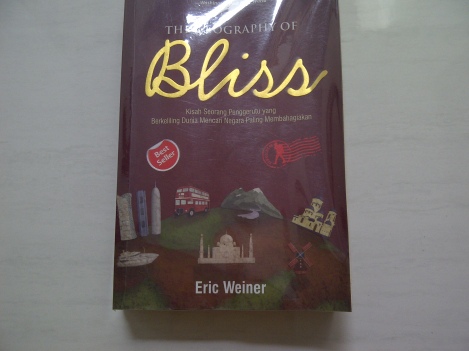Konon katanya, orang
bergolongan darah B cenderung untuk menjadi cat
person. Secara umum, memang hampir semua teman B yang saya kenal adalah
penyayang binatang. Dengan dua perkecualian. Saya punya dua orang teman bergolongan darah B yang justru phobia pada kucing. Mungkin tepatnya
begini: orang yang bergolongan darah B cenderung memiliki hubungan emosional
dengan kucing. Bisa positif atau negatif. Tapi saya bukan hendak membahas
golongan darah di sini. Saya hanya akan bercerita tentang hubungan emosional
saya sendiri dengan kucing.
Sejak saya masih sangat kecil,
seingat saya rumah ini sering dianggap tempat bersalin kucing. Mungkin karena
memang rumah ini berantakan, ada sudut-sudut yang memungkinkan dipakai induk
kucing untuk beranak. Mungkin juga karena kami para penghuni rumah ini relatif
baik pada kucing. Tidak memanjakan, tapi juga bukan orang-orang kejam yang suka
mengusir kucing dengan menyiram air panas (atau bahkan minyak panas!). Tak
pelit berbagi makan, meski hanya tulang ikan.
Jadi hampir setiap musim kucing
beranak, ada bayi kucing di rumah ini. Hanya numpang beranak, lalu sang induk
memindahkan bayi-bayi kucing entah ke mana. Mitos yang beredar di kampung kami,
bayi kucing akan dibawa pindah tujuh kali oleh induknya. Ini semua dilakukan
demi keamanan bayi-bayi kucing dari ancaman ayah mereka. Saya sendiri tak
pernah melihat kejadian menyeramkan kucing pejantan memangsa bayi-bayinya, sih.
Tapi bahwa induk kucing rajin sekali memindahkan bayi, saya menjadi saksi.
Kucing yang sampai besar ada di
rumah adalah dua bersaudara si Ireng dan si Merah. Sebenarnya si Merah ini
berwarna orange, tapi entah mengapa bagi orang kampung saya warna kucing
seperti itu disebut merah. Mereka berdua menjadi teman-teman saya sejak masih bayi,
sedangkan saya kelas 3 SD. Dengan merekalah saya pertama kali mengajak kucing
mengobrol. Biasanya kata-kata saya pada kucing mana pun hanya instruksi atau
memberi makan.
Si Ireng ini hampir seluruh
tubuhnya berwarna hitam, kecuali bagian perut dan keempat kakinya (sehingga
terlihat seperti mengenakan kaos kaki). Dia kucing yang garang, terlihat
maskulin sejak masih bocah. Ahli dalam berburu tikus, bahkan dari usianya
sangat muda. Saudaranya, si Merah, relatif lebih pendiam. Waktu masih bayi,
kami mengira dia adalah kucing betina. Begitu memasuki usia beberapa bulan,
barulah tampak kejantanannya.
Saat kelas empat SD, saya
pernah menangis sesorean karena si Ireng tidak dapat ditemukan di mana pun.
Bapak dan ibu ikut panik, karena saya bukan tipe anak yang gampang menangis.
Mereka dibantu kakak, sibuk mencari ke mana-mana. Saya tetap menangis di rumah,
ditemani si Merah yang bingung melihat kelakuan saya. Rupanya si Ireng tak
pergi jauh, hanya ikut nonton tivi di rumah tetangga sebelah. Saya memeluknya
sambil menangis saat bapak membawanya pulang.
Bapak memberi petuah panjang bahwa
memang begitulah kucing, saya tak boleh melarangnya bermain. Selama ini mereka
ada di rumah karena memang masih kecil. Selanjutnya mereka akan mulai
bertualang, berburu, tidur di atap melindungi rumah kami dari tikus. Kucing itu
bukan boneka yang bisa dimiliki sepenuhnya. Mereka punya kehidupan sendiri. Tak
terlalu mengerti, saya mengusap air mata sambil tetap memeluk si Ireng.
Petuah Bapak benar juga,
setelah itu kedua anak kucing manis rumahan itu mulai rajin pergi. Hanya pulang
kalau lapar saja. Waktu itu rasanya kesal sekali, seperti diabaikan oleh
sahabat. Tapi lama kelamaan saya juga sibuk dengan teman-teman manusia, tugas
sekolah dan berbagai lomba yang mulai saya ikuti. Sesekali masih ngobrol dengan
mereka, terutama si Ireng, kalau kami sedang sama-sama di rumah.
Masa kecil saya cukup ‘rusak’
gara-gara kelakuan teman-teman berbulu ini. Di kelas lima, untuk pertamakalinya
saya mengenal konsep hubungan sesama jenis. Si Ireng dan si Merah yang
sama-sama pejantan melakukan adegan mesum! Sudah incest, gay pula. Awalnya saya
syok, dan memarahi mereka berdua. Tapi mereka tak pernah peduli, tetap saja
mempertontonkan adegan mesum itu pada anak di bawah umur seperti saya. Hih!
Lewat masa SD, saya benar-benar
sibuk dengan dunia saya sendiri. Si Ireng dan si Merah pun mengurusi hidup
mereka sendiri. Kami semakin jarang bertemu. Tapi mereka memberi pengalaman
pertama tentang pertemanan saya dengan kucing. Musim-musim berikutnya, rumah ini
masih dipakai para induk untuk beranak. Tak ada lagi yang menetap sampai
dewasa. Hanya numpang lahir lalu pindah lagi, seperti sebelum kedatangan dua
teman saya.
Saat masuk SMA, saya
meninggalkan rumah dan kos di luar kota. Tentu, tak boleh membawa piaraan di
rumah kos.Bertahun-tahun lamanya saya hanya jadi pemerhati kucing, yang rajin
menyapa setiap kucing yang saya temui di jalan. Herannya, para kucing seperti
memahami apa yang saya katakan. Baru saat menjelang tingkat akhir kuliah, saya
kembali punya teman berbulu. Si Thoyyib yang sudah pernah saya ceritakan di
sini sebelumnya.